 Judul :
Di Tanah Lada
Judul :
Di Tanah Lada
Pengarang
: Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie
Tahun
terbit : Oktober 2015
Penerbit
: PT. Gramedia Pustaka Utama
Jumlah
halaman : 244 halaman
Sinopsis
Namanya Salva. Panggilannya Ava. Namun
papanya memanggil dia Saliva atau ludah karena menganggapnya tidak berguna. Ava
sekeluarga pindah ke Rusun Nero setelah Kakek Kia meninggal. Kakek Kia, ayahnya
papa, pernah memberi Ava kamus sebagai hadiah ulang tahun yang ketiga. Sejak itu
Ava menjadi anak yang pintar berbahasa Indonesia. Sayangnya, kebanyakan orang
dewasa lebih menganggap penting anak yang pintar berbahasa inggris. Setelah pindah
ke Rusun Nero, Ava bertemu dengan anak laki-laki bernama P. Iya, namanya hanya
terdiri dari satu huruf P. Dari pertemuan itulah, petualangan Ava dan P bermula
sampai pada akhir yang menakjubkan.
Saya tidak
tau, apakah tulisan ini berujung pada sebuah review atau sejenisnya. Tetapi,
saya berharap setidaknya saya ingin memperkenalkan buku ini pada banyak orang.
Saya menemukan beberapa teman-teman di goodreads memasukkan buku ini ke dalam
rak want-to-read atau saya mendapati
mereka currently-reading this book. Saya
akui, saya tidak tertarik membacanya, karena berhubungan dengan ‘anak kecil’
yang dalam mindset saya bercerita tentang dongeng-dongeng klasik. Tetapi,
kenapa saya memutuskan untuk membacanya? Secara tidak sengaja, ketika scroll
daftar buku di Ijak, I found it. Di
sana, ratingnya cukup tinggi, lalu saya baca review pembaca di goodreads, dan
mereka juga memberikan respon positif. Akhirnya, saya memutuskan untuk
meminjamnya di Ijak.
Saya
takjub dengan penulis buku ini. Kenapa? Entah bagaimana ia mampu menulis hingga
saya merasa yang bercerita itu memang anak berusia 6 tahun. Pada bagian awal
saya sudah tertawa sendiri karena kepolosan anak yang bernama Ava. Saat berusia
tiga tahun, Kakek Kia—ayahnya papa Ava memberikannya kamus Bahasa Indonesia.
Oleh karena itu, setiap Ava menemukan kata-kata yang tidak dipahaminya, ia akan
mencari di dalam kamus. Namun, bukan itu yang membuat saya tetap melanjutkan
membacanya, melainkan karena prilaku papa Ava yang tidak menganggap ia anaknya
dengan baik, bahkan seringkali memukulinya tanpa sebab. Di sini, penulis dengan
sudut pandang Ava bercerita betapa tidak-sukanya ia dengan papanya.
Awal
kisah gadis kecil itu bermula saat Kakek Kia meninggal dan meninggalkan harta
kepada anaknya. Lalu, Ava, mama, dan papanya memutuskan untuk pindah ke Rusun
Nero. Di sanalah ia bertemu dengan anak laki-laki berumur 10 tahun bernama P.
Jujur, saat saya tau siapa nama anak laki-laki itu, kening saya berkerut. Only P? Ya, namanya P. Namun Kak Suri—orang yang
mengajari laki-laki itu bahasa inggris memanggilnya Prince, dan begitu juga Om
Alri (silahkan dibaca siapa itu om Alri? ^^). Namun, Ava tidak ingin
memanggilnya Prince. Ava memanggil laki-laki itu dengan sebutan Pepper yang berarti lada, sedangkan ia
menginginkan dipanggil Salt yang
berarti garam. Filosofi sederhananya bahwa jika makan tanpa lada hanya dengan
garam, tidak masalah, tetapi akan lebih baik makan dengan garam, karena akan
terasa lebih enak. Kapan petualangan mereka dimulai? Saat suatu insiden menimpa
Pepper yang menyebabkan mereka pergi,
ingin bahagia dengan cara mereka sendiri.
Miris
sebenarnya, ketika anak yang berusia sangat dini harus mengalami hal-hal
mengerikan semacam itu. Seharusnya di usia itu, mereka dapat bermain sesuka
hati, melakukan banyak hal yang menyenangkan, tanpa berpikir lebih banyak. Tetapi
Ava dan P tidak begitu. Saya rasa pengaruh lingkungan keluarga menghadapkan
mereka untuk berpikir tidak seusianya. Bayangkan di usia yang sangat dini,
mereka telah melahirkan pemikiran yang skeptis atas apa yang mereka ketahui. Mereka
menganggap bahwa di dunia ini, semua papa
jahat, semua mama lupa dengan anaknya. Mereka selalu berbicara tentang
reinkarnasi, menginginkan hidup di masa lalu yang lebih baik, atau bahagia di
masa mendatang.
Seandainya
ending yang disajikan penulis tidak seperti ini, setidaknya ada sesuatu yang
membuat mereka bahagia setelah semua yang terjadi. Bagaimanapun, mereka juga
berhak untuk bahagia. Tetapi, sekali lagi—ini hanyalah fiksi, dimana penulis
berhak atas cerita yang ia tulis. Meskipun begitu, saya memaklumi kenapa mereka
berdua memutuskan akhir hidup mereka seperti itu. Mungkin, mereka sudah terlalu
lelah. Ah, buku ini sangat kelam,
sungguh.
Pada
bagian akhir tentang sehidup semati,
saya merasa tiba-tiba bukan Ava lah yang bercerita. Tadinya saya berpikir
tulisan di akhir bab ketika Ava berusia remaja, karena gaya penuturannya sudah
berbeda. Ternyata, tidak. Gadis itu masih berusia 6 tahun. Tiba-tiba di akhir
buku seorang Ava disulap menjadi gadis berusia 17 tahun. Ah, saya sedikit
bingung. Seharusnya, jika mereka tetap anak-anak, hingga akhirpun tetap harus
disudahi bahwa mereka hanyalah anak-anak.
Tidak
banyak yang ingin saya ceritakan pada tulisan kali ini, tetapi sepertinya
esok-esok akan saya baca karya Ziggy yang lain. Saya ingin sekali memberikan
5/5 bintang, tetapi ada sesuatu yang menahan saya, sehingga saya memutuskan 4/5
bintang adalah cukup untuk buku ini. Anehnya, saya berterimakasih kepada
penulis, karena di akhir liburan panjang ini saya mendapatkan sesuatu lagi.
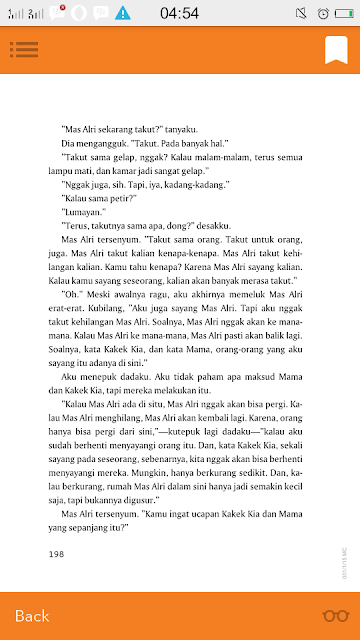




No comments:
Post a Comment